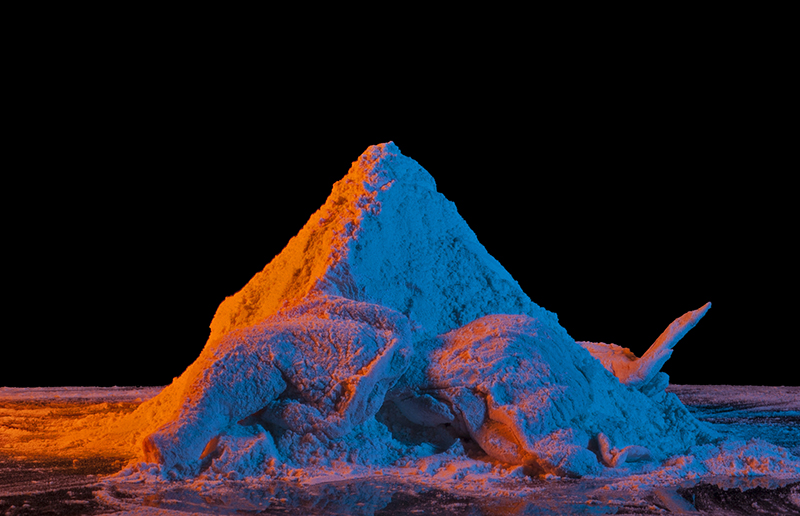Suatu siang, saya dan seorang teman akrab saya, melalui pesan di Whatsapp, merencanakan sore nanti akan makan di restoran Olive Chicken.[1] Bagi saya rencana makan ini biasa saja, lebih pada agenda ngobrol ngalor–ngidul berdua, lebih intim dan seru yang isinya membicarakan kesibukan diri sendiri dan tentu saja kesibukan orang lain yang lebih menarik alias bergosip sambil makan ayam goreng tepung. Ketika tiba di restoran Olive Chicken, teman saya langsung meyakinkan untuk memesan 4 potong ayam; 2 paha atas, 2 sayap serta 1 nasi, dan 2 es teh. Alasannya separuh porsi nasi dan 1 ayam paha atas cukup sebagai menu utama untuk kami masing-masing karena kami tidak begitu lapar. Lalu sayap ayam sebagai penutup, karena pada potongan sayap ayam banyak terdapat bagian yang gurih dan crispy, kata teman saya. Konsepnya dalam menikmati makanan adalah “save the best for last” atau kata orang Jawa untuk gong. Saya sepakat dengan idenya. Saat memulai makan, teman saya mengawali dengan kalimat,“Ayam Olive ini lebih enak dari ayam KFC yang crispy, lho…” dan dilanjutkan dengan,“Tapi kalau dibanding yang rasa original, KFC tetap yang paling enak dan orisinal, sih!”. Saya mengiyakan dengan mengangguk-angguk sambil ber-“oooo” panjang.
Sejujurnya saya tidak begitu paham dan merasakan perbedaan antara dua varian rasa dari produk ayam KFC, yang original dan crispy. Selain karena saya jarang makan di KFC, saya juga cukup abai saat menikmati, merasakan, dan membandingkan kedua jenis varian ayam tersebut. Menurut saya, hal itu bukan suatu pengetahuan yang cukup penting dalam menjalani hidup, tidak seperti pengetahuan bagaimana menghapus malware dari laptop atau mengganti busi pada motor. Tetapi saya kemudian tertarik ketika mendengar kata orisinal, selain enak, menjadi kata keterangan yang dibubuhkan pada sepotong ayam goreng tepung. Selain itu, karena komentar ini setidaknya pernah tiga kali saya dengar dari orang yang berbeda saat membicarakan ayam goreng tepung dari produk restoran fast food. Ini membuat saya ingin mencari tahu lebih dalam. Apakah yang dimaksud dengan orisinal dalam makanan? Saya lalu melakukan observasi kecil-kecilan terhadap beberapa produk ayam goreng tepung fast food dan komentar orang-orang.
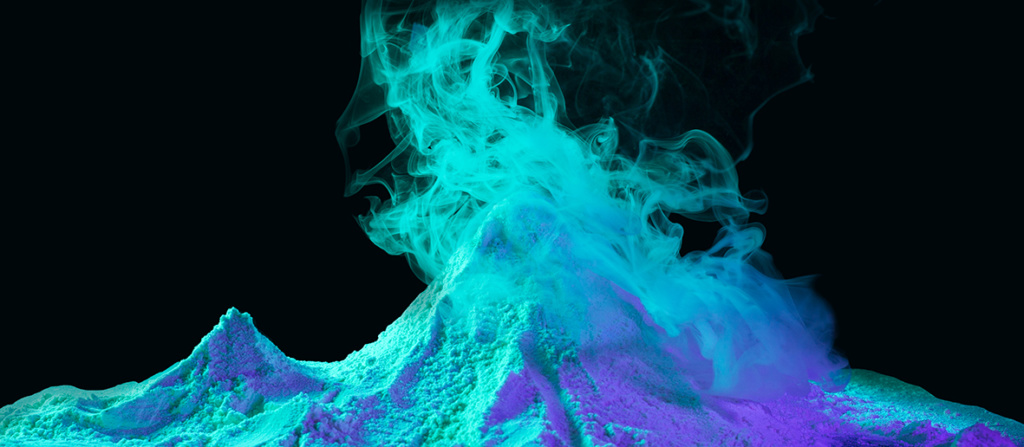
Sebelumnya, istilah fast food sendiri yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi makanan cepat saji, memiliki cakupan yang sangat luas. Selain akrab dengan bentuk-bentuk makanan seperti ayam goreng, kentang goreng, hamburger dan sejenisnya, fast food juga bisa diterjemahkan menjadi makanan jenis apapun asalkan disajikan dengan cepat setelah dipesan. Misalnya mi instan di warmindo, nasi dan lauk di rumah makan padang, bakso atau mi ayam di warung kaki lima, dan sebagainya. Dalam bahasan ini, saya akan membatasi istilah fast food bukan hanya sebagai makanan yang dimasak dan disajikan dengan cepat. Istilah fast food di sini juga merujuk pada produk-produk waralaba dengan karakteristik menu tertentu seperti ayam goreng, hamburger, kentang goring, dan sebagainya, yang sebagian proses memasaknya sudah dilakukan di pabrik-pabrik serta memiliki standar rasa yang sama di setiap gerainya. Selain itu tata cara memesannya dilakukan di counter yang juga berfungsi sebagai kasir untuk kemudian dimakan di tempat atau dibawa pulang. Saya akan menggunakan istilah “fast food internasional” untuk menyebut restoran waralaba yang lahir dan berasal dari luar Indonesia seperti McD, KFC, Wendy’s, Burger King, Pizza Hut, dan Dunkin Donuts, dan istilah “fast food lokal” digunakan untuk merujuk jenis restoran yang menggunakan sistem sama dengan fast food internasional, tetapi dibangun oleh pengusaha lokal yang biasanya bisnisnya berada di tingkat kota atau propinsi, maupun nasional.
Pengalaman awal kita mengonsumsi menu-menu seperti ayam goreng tepung dan hamburger, kemungkinan terjadi pada saat masuknya restoran-restoran fast food internasional di sebagian besar negara Asia, termasuk Indonesia. Tercatat pertama kali restoran waralaba KFC dibuka di Indonesia tahun 1979 di Jalan Melawai, lalu Pizza Hut pada tahun 1984, McDonalds pada tahun 1989 di Sarinah dan diikuti Dunkin Donuts pada awal 1990. Semua gerai tersebut dibuka pertama kali di kota Jakarta. Bisa dibayangkan pada kurun tahun 80-90-an merupakan masa-masa selera kita akan produk-produk makanan tersebut “terbentuk”. Gempuran iklan baik di majalah, televisi, maupun papan reklame turut menyumbang rasa penasaran yang akhirnya mendorong kita menjatuhkan pilihan makan pada produk Amerika tersebut. Seingat saya, harga untuk makan di restoran fast food internasional ini masih terbilang cukup mahal untuk sebagian besar penduduk Indonesia pada waktu itu. Ibu saya membolehkan makan fast food, yang waktu itu pilihan antara KFC atau Texas Fried Chicken, hanya di waktu-waktu tertentu saja, bukan karena isu tidak sehat yang ramai dibicarakan saat ini, melainkan karena harganya yang cukup mahal dan menurutnya pemborosan.
Kembali membicarakan tentang rasa yang enak dan orisinal pada ayam goreng tepung yang tentu saja istilah enak bersifat sangat relatif. Tidak pernah ada makanan yang enak atau tidak enak secara absolut. Secara ilmiah, kita dapat merasakan berbagai rasa, seperti asin, manis, pahit, dan asam karena kita memiliki lidah yang berfungsi sebagai reseptor. Bagaimana lidah bekerja, menurut Brillat Savarin dalam bukunya The Physiology of Taste, sensasi dalam rasa atau kegiatan merasakan merupakan sebuah proses kimiawi yang dihasilkan dari kelembaban atau “humiditas”. Partikel-partikel rasa harus larut dalam cairan, dalam hal ini dilakukan oleh air ludah sehingga bisa meresap ke permukaan lidah yang terdiri dari sekumpulan saraf dan tendril yang merupakan selubung dari organ pengecap.[2] Baru kemudian saraf lidah mengirim sinyal ke otak untuk mengolah data tersebut. Dalam menghasilkan data, seringkali lidah dibantu oleh mata yang menjelaskan bentuk fisik dan tekstur benda serta indra penciuman yang turut membantu menjelaskan keberadaan benda tersebut lewat bau. Dalam hal ini, aktivitas merasakan atau makan bisa dilihat sebagai pengalaman individu yang sangat subjektif dan personal. Tetapi, sebagai sebuah organ pengecap utama, ternyata lidah tidak bekerja secara otonom dalam menentukan rasa yang enak atau tidak enak. Selain dibantu indra lainnya, fungsi otaklah yang paling dominan dalam mengevaluasi rasa yang membuatnya cukup kompleks.
Makan merupakan sebuah pengalaman kultural yang membentuk pengetahuan kolektif saat otak akan memberi tahu apakah benda ini baik atau buruk, enak atau tidak enak untuk dimakan yang ditentukan oleh banyak faktor. Sebagai sebuah kegiatan yang sudah ada sejak kita lahir, pengetahuan tentang makan dan makanan terbentuk bersama dengan berbagai variabel, seperti ilmu pengetahuan, agama, budaya, kesehatan, ekonomi, yang kemudian didefinisikan sebagai “nilai-nilai” yang sifatnya positif dalam masyarakat.[3] Karena berbagai variabel dalam masyarakat ini sifatnya tidak kekal dan berubah dari waktu ke waktu, maka pengetahuan kita akan rasa dan selera juga merupakan sebuah konstruksi budaya yang dapat berubah. Bisa dikatakan, rasa merupakan sesuatu yang tidak hadir secara alamiah, tetapi lebih merupakan suatu proses bentukan dari masyarakat yang kemudian saling berpantulan dengan pengalaman personal dengan begitu kompleksnya. Termasuk anggapan kita bahwa ayam goreng tepung KFC yang paling enak dan orisinal, mungkin terbangun atas pengalaman dan pengetahuan mengonsumsi KFC dengan segala nilai dan atribut yang meyertainya.
Sedangkan istilah orisinal, yang menurut KBBI berarti asli atau tulen, saya duga muncul sejalan dengan populernya salah satu produk KFC, yaitu ayam goreng Colonel’s Original Recipe, yang juga merupakan produk unggulan dari waralaba KFC. Konon katanya, ayam ini dibuat dari resep asli Kolonel Sanders yang tidak bisa ditiru oleh ayam goreng tepung lain. Menurut profil yang tertera dalam situs web KFC, produk Colonel’s Original Recipe dan Hot & Crispy, merupakan produk ayam goreng paling disukai dan dinilai sebagai ayam goreng paling enak versi berbagai survei konsumen di Indonesia. Selain itu, BITS (Brand Image Tracking Studies) survei, yang dilakukan oleh lembaga survei independen menunjukkan KFC secara konsisten masih menempati posisi tertinggi “paling diingat” oleh konsumen untuk Top of Mind Awareness dibanding usaha waralaba sejenis.[4] Hal ini bisa menunjukan kepopuleran KFC berserta produk ayam goreng tepungnya dibanding produk-produk sejenis dari fast food lain.

Saya tertarik dengan munculnya kata orisinal dalam sepotong ayam, seolah jika ada yang orisinal, maka ada yang tidak orisinal. Kata orisinal tentunya kita sadari merupakan tagline dari usaha dagang KFC untuk melegitimasi ayam goreng tepung dengan resep rahasia Kolonel Sanders. Dengan begitu, kata orisinal merujuk pada penggunaan resep rahasianya, bukan ide tentang ayam goreng tepung sendiri. Jika ada berjuta-juta ayam goreng tepung di dunia ini, bisa jadi semua orisinal selama tidak dibuat dengan tujuan untuk mereplika dari resep Kolonel Sanders. Mungkin di sinilah ide tentang yang non-orisinal hadir, sejalan dengan kepopuleran KFC sebagai kanon ayam goreng tepung yang enak sehingga banyak usaha terang-terangan untuk meniru resep Kolonel Sanders muncul. Kata Kentucky yang diambil dari merek Kentucky Fried Chicken yang merujuk pada suatu tempat di negara Amerika Serikat sana, selain merupakan tempat lahirnya restoran KFC, juga diadopsi menjadi nama sebuah bentuk masakan atau metode memasak, yaitu menggoreng dengan tepung bumbu.
Ada banyak sekali produk tepung bumbu di pasaran yang lebih akrab disebut “tepung Kentucky”, di antaranya dari merek Kobe, Sajiku, Masako, dan lain-lain. Selain itu ada banyak resep, baik di majalah dan tabloid wanita maupun buku resep tersendiri yang menyajikan resep dan tips membuat ayam goreng ala KFC semirip mungkin, maupun berbagai macam bahan yang bisa diolah dengan “tepung Kentucky”. Rezim ayam goreng tepung yang tadinya hanya bisa dinikmati di restoran-restoran yang berada di mal atau kota besar, telah menyebar hingga ke dalam dapur privat rumah tangga baik di kota besar maupun kota kecil, dalam bentuk peniruan. Saya ingat, “tepung Kentucky” merupakan andalan ibu saya saat kami ingin makan ayam goreng KFC tapi uang belanja pas-pasan. Waktu itu ibu saya mencoba dari berbagai merek tepung bumbu, kemudian saya dan kakak saya sepakat bahwa tepung Kobe-lah yang paling enak. Alasannya karena paling mirip dengan KFC yang asli.

Proses peniruan ini tanpa disadari terus berlanjut dan kerap diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat negatif, terutama jika hasil dari tiruan ini diperjualbelikan untuk alasan ekonomi. Kegiatan meniru atau menggandakan sesuatu seolah mengurangi nilai esensi dari benda asalnya. Padahal bisa jadi memang semua benda pada awalnya tidak pernah punya esensi. Manusialah yang kemudian melekatkan dan membubuhi benda-benda tersebut dengan nilai-nilai yang sarat makna untuk berbagai kepentingan. Beratus-ratus ayam goreng KFC di atas rak dalam gerainya hanyalah seonggok ayam goreng. Jangankan ayam goreng, lukisan Picasso pun hanyalah sebuah gambar yang tak punya makna, sebelum diberi berbagai macam nilai oleh otoritas yang berhak, seperti ahli seni, sejarawan, museum negara, dan sebagainya.
Sama halnya dengan seonggok ayam tadi, dia jadi punya makna ketika diberi identitas ayam KFC yang dibuat di dapur legal tempat setiap potong ayam KFC seharusnya diproduksi, diracik sesuai resep Kolonel Sanders dan dijual dengan nilai ekonomi tertentu. Begitu juga dengan seratus orang ibu yang sedang membuat resep ala KFC yang didapatnya dari majalah Femina akan menghasilkan seratus ayam goreng tepung yang dinilai sebagai ayam goreng tepung ala KFC yang berusaha menirunya, bukan dan tidak akan pernah menjadi ayam goreng KFC.
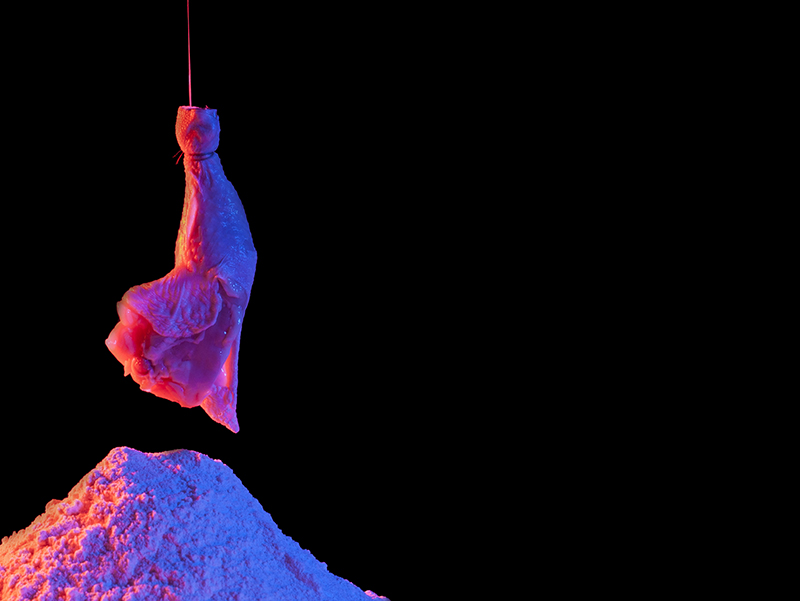
Kegiatan menciptakan ayam goreng tepung secara swadaya ini kemudian semakin meluas dan terlembaga dalam bentuk restoran, yang ternyata menggunakan konsep berjualan yang hampir sama. Sepengetahuan saya, restoran ayam goreng tepung sejenis yang dibuat oleh pengusaha lokal dengan sistem waralaba dan jenis restoran seperti fast food internasional atau lebih tepatnya seperti KFC, terjadi di kota-kota lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia, Texas Fried Chicken serta California Fried Chicken atau CFC merupakan fast food lokal yang bisa dijadikan contoh.
Contoh lain di kota Beijing, sesudah gerai pertama KFC dibuka dan menuai kesuksesan, muncul beberapa fast food lokal yang meniru, seperti Lingzhi Roast Chicken, yang diikuti Chinese Garden Chicken, Huaxiang Chicken, dan Xiangfei Chicken hingga yang paling terkenal Ronghua Fried Chicken. Fenomena tersebut dikenal dengan nama “war of fried chickens”.[5] Bentuk-bentuk ini secara umum kerap dilihat sebagai bentuk imitasi, karena diyakini meniru habis-habisan, terutama dari menu dan rasa makanannya, konsep menjual hingga karakter dari restoran-restoran tersebut.
Dalam jurnal Of Hamburger and Social Space: Consuming McDonald’s in Beijing, Yungxiang Yang menyebutkan :“All of the local fried chicken variations were no more than simple imitations of the KFC food. Their only localizing strategy was to emphasize special Chinese spices and sacred recipes that supposedly added an extra medicinal value to their dishes. Thus, consumers were told that the Chinese Garden Chicken might prevent cancer and that Huaxiang Chicken could strengthen the yin-yang balance inside one’s body”.[6]
Kata imitasi sendiri menurut KBBI berarti tiruan, bukan asli. Dalam contoh penggunaanya tertulis sebagai berikut: kalung imitasi, kalung yang dibuat bukan dari emas, tetapi warnanya menyerupai emas. Kemudian disertai contoh lain; sastra imitasi, karya sastra tiruan (secara sengaja) dari karya sastra lain. Berdasarkan contoh tersebut, terlihat adanya unsur kesengajaan dan usaha dalam mengimitasi serta adanya benda acuan yang telah hadir sebelumnya sebelum proses imitasi berlangsung. Sebuah benda yang secara tak sengaja hampir sama atau mirip tidak bisa dikatakan imitasi atas benda lainnya. Selain itu, benda imitasi membutuhkan pendahulunya untuk dikatakan sebagai yang orisinal atau yang ditirunya. Dengan demikian orisinal dan imitasi merupakan relasi antarobjek yang dibangun manusia untuk disusun dan diposisikan sedemikian rupa. Lalu bagaimana awalnya ayam goreng tepung ini muncul? Siapa yang paling orisinal dari yang orisinal?
Sejarah ayam goreng tepung sendiri yang sebelumnya dikenal dengan sebutan “southern fried chicken”, awalnya dibuat oleh para budak di Amerika, seperti yang diceritakan sebagai berikut:
“Potongan ayam yang dibalur tepung dan kemudian digoreng dalam lemak panas. Istilah southern fried pertama kali muncul dalam bentuk cetak pada tahun 1925…tentu saja orang-orang selatan bukanlah yang pertama dalam menggoreng ayam. Hampir setiap negara sudah memiliki versinya masing-masing, dari mulai Ga Xao di Vietnam, Pollo Frito di Italia, dan Weiner Backhendl di Austria serta masih banyak jenis gorengan yang disajikan dengan saus kental (fricassee) yang termuat dalam sejumlah buku resep masakan di Eropa. Sementara ayam goreng belum populer di Amerika Serikat bagian utara hingga memasuki abad ke-19. Orang-orang Skotlandia yang lebih menyukai menggoreng ayam dibanding merebus atau memanggangnya seperti yang umum dilakukan orang Inggris, kemungkinan yang membawa metode dan teknik ini bersamaan dengan kepindahan mereka ke selatan. Proses memasak yang efisien dan sederhana ini kemudian sangat cocok diterapkan dalam kehidupan perkebunan oleh budak-budak Afrika-Amerika Selatan yang sering diizinkan untuk memelihara ayam mereka sendiri. Ide untuk membuat saus yang disajikan dengan ayam goreng ini sudah muncul sebelumnya, paling tidak di Maryland, tempat perpaduan ini dikenal dengan nama “ayam goreng Maryland”. Pada 1878 hidangan dengan nama tersebut tercantum dalam daftar menu di Hotel Grand Union di Saratoga, New York…”[7]
Keinginan manusia untuk melacak dan mencari tahu asal muasal suatu benda selalu ada, termasuk dalam resep dan budaya makan yang ternyata bukanlah perkara mudah. Terlebih lagi kita tahu bahwa dunia yang maha luas ini tidak berjalan dengan linear dan beraturan sebab penemuan-penemuan, ilmu pengetahuan, dan akses terhadapnya tidak tersebar merata.
Berdasarkan sumber di atas, kemudian kita jadi tahu bahwa Kolonel Sanders tidak menciptakan ide tentang resep ayam goreng KFC benar-benar dari nol, dari ketiadaan atas apapun. Kolonel Sanders juga melakukan sebagian dari proses mengimitasi atas apa yang telah dilakukan oleh budak-budak di selatan Amerika yang mungkin juga sudah dipraktikkan jauh sebelumnya oleh para ibu di Vietnam, menggoreng ayam. Ide tentang ayam goreng tepung pertama mungkin saling silang sengkarut dengan saat dimulainya manusia mulai menjadikan ayam sebagai hewan ternak dan sumber protein, penemuan teknik memasak dengan menggoreng, keberhasilan mengubah biji gandum menjadi tepung, penyebaran bumbu-bumbu lewat perdagangan dan sebagainya. Bisa dikatakan resep Kolonel Sanders tidak 100% original. Sama halnya dengan yang dibuat oleh restoran-restoran fast food lokal lain.
Proses mengimitasi yang berjalan paralel di berbagai lokasi ini kemudian juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia dalam skala usaha yang lebih kecil. Di Yogyakarta sendiri seingat saya, fast food lokal yang menyajikan ayam goreng tepung pertama kali diinisiasi oleh Jogja Chicken (sekarang berganti nama menjadi Golden Fried Chicken) yang mulai beroperasi sekitar tahun 1999, diikuti oleh restoran-restoran sejenis lain. Ada Kentuku Fried Chicken, yang namanya benar-benar terdengar parodi atau plesetan khas Yogyakarta, hingga yang baru-baru ini muncul seperti Popeye Chicken dan Olive Chicken. Lalu apa yang membuat ayam goreng tepung KFC masih diyakini sebagai ayam yang paling orisinal dan yang lain berupa imitasi atasnya?
Ada beberapa faktor yang menggiring kita untuk berpikir demikian. Misalnya untuk kasus di Indonesia, terlihat dari pilihan untuk menggunakan nama suatu daerah di Amerika seperti Texas atau California sebelum frasa “fried chicken”, seperti halnya Kentucky, yang tentunya terjadi setelah KFC membuka gerainya di Indonesia. Selain itu, banyaknya resep yang diterbitkan secara terang-terangan untuk membuat ayam goreng KFC tersebar begitu banyak di media, yang membuat kita beranggapan semua kegiatan membuat dan menjual ayam goreng tepung adalah sedang meniru KFC. Ditambah harga dari menu-menu fast food lokal ini jauh lebih murah untuk makanan yang sama, seolah sebagai produk imitasi maka nilainya tidak sebanding dengan yang orisinal. Sebagai perbandingan, jika satu paket nasi ayam KFC yang terdiri dari nasi, ayam original dan 1 minuman soda seharga 35 ribuan, maka di Olive satu paket ayam, nasi, dan 1 gelas es teh hanya seharga 9 ribu. Selain lebih murah, restoran-restoran fast food lokal yang berada di Yogyakarta ini juga tidak semenarik dan senyaman fast food internasional; tanpa pendingin ruangan, sound yang kurang memadai atau tanpa musik, lantai yang sering kotor dan tidak mengilap, hingga furnitur yang kadang seadanya dan dekorasinya berupa printoutdoor dengan visual makanan yang diambil dari internet entah milik siapa.
Secara kasat mata, fast food lokal sepertinya menyasar pada pasar dengan kelas ekonomi bawah yang tidak terwadahi oleh fast food internasional. Dengan memosisikan dirinya untuk kelas tersebut, kesenjangan antara yang asli atau orisinal dengan yang tiruan semakin terasa dan semakin melanggengkan posisi-posisi yang demikian hierarkis dalam perihal keaslian di kancah per-fast food-an. Seolah yang orisinal, yang diwakili oleh fast food internasional berada di atas fast food lokal yang dilekatkan dengan produk imitasi. Apalagi perkara orisinal dan imitasi dalam produk budaya cukup lekat dengan permasalahan kelas ekonomi. Ada stigma dalam masyarakat bahwa konsumsi barang-barang imitasi memang diperuntukkan kaum kelas bawah yang tidak mampu membeli yang orisinal. Faktor-faktor ini kemudian membentuk sekumpulan nilai yang terus menerus baik secara sadar maupun tidak ada di benak kita.

Catatan Penutup
Saya teringat sensasi pengalaman makan di gerai KFC sewaktu saya masih bersekolah di sekolah dasar, di awal tahun 90-an. Mulai dari pendingin ruangan yang membuat suhu ruangnya menjadi sejuk, baunya yang khas antara bau ayam yang sedang digoreng bercampur bau pembersih lantai dan sabun cuci tangannya yang harum, serta makan di dalam gerai yang muka bangunannya dikelilingi kaca sehingga kita bisa menonton pemandangan di luar dengan suara latar musik yang terkadang memutar jingle KFC.
Selain sensasi yang saya rasakan dari indra-indra tersebut, ada sensasi lain yang saya ingat, sensasi menjadi manusia modern. Menjadi bagian dari masyarakat yang teratur yang kala itu merupakan hal baru. Saya ingat bagaimana harus bertingkah laku mulai saat masuk gerai, mengantre di depan counter untuk memesan menu, menunggu sebentar hingga menu siap dan membayar. Setelah itu membawa makanan kita sendiri ke meja, lalu mengambil saus dan segala perlengkapan makan sebelum mulai makan. Tidak dilayani oleh pelayan restoran. Semua dilakukan atas kesadaran dan usaha sendiri, bahkan hingga membuang sisa makan di tempat sampah dan mengembalikan nampan. Sungguh ritual ini mencerminkan kumpulan masyarakat mandiri yang teroganisasi dengan baik alias masyarakat modern. Ide tentang manusia modern ini tidak begitu saja muncul dari pikiran saya, tapi saya dapat dari iklan di televisi, pembicaraan orang-orang akan pengalamannya makan di gerai fast food yang kemudian saya refleksikan dengan pengalaman pribadi saya. Begitu juga saya rasa dengan ide akan ayam goreng tepung yang orisinal.
Kita sadar bahwa orisinalitas tidak dengan sendirinya hadir di dunia ini. Orisinal dan imitasi adalah istilah-istilah yang diciptakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang kemudian terus menerus mereproduksi gagasan ini. Tentu saja ada berbagai kepentingan dibalik ide ayam orisinal dari KFC. Selain kepentingan ekonomi dan bisnis, kepentingan ideologi misalnya. Sebagai produk budaya global yang selalu diidentifikasi sebagai komoditas Amerika, kita tahu bagaimana industri fast food menancapkan jaring-jaring kapitalisme dalam menjalankan perusahannya, termasuk menjadi manusia modern dan menjual pengalaman serta cara hidup ala Amerika.
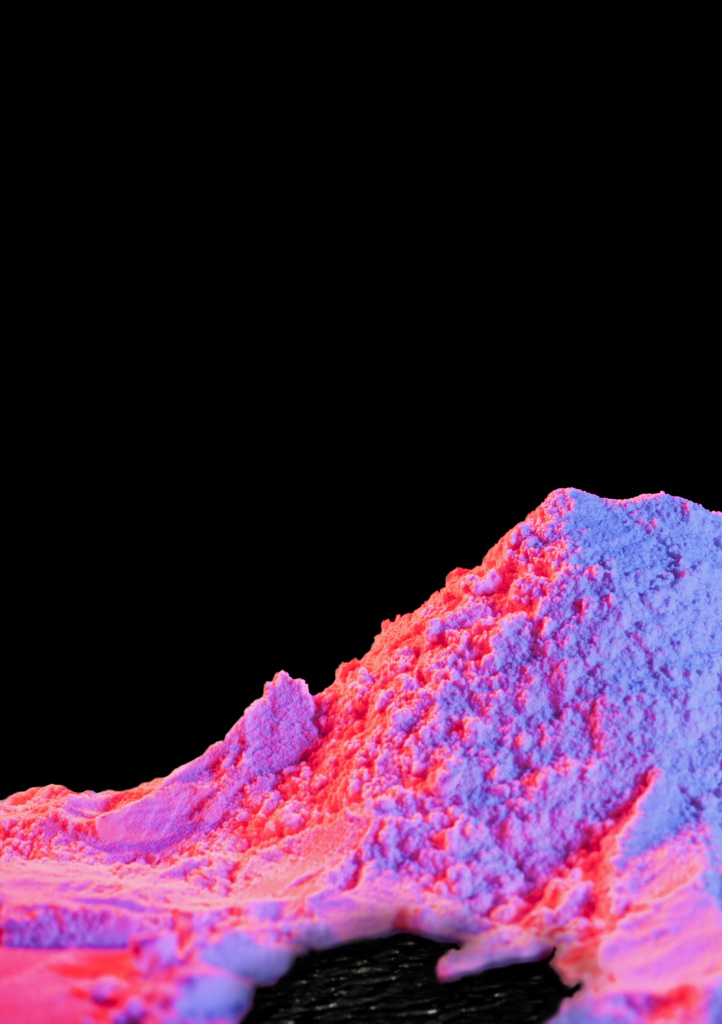
Setelah bertahun-tahun, dimulai sejak hari pertama saat gerainya dibuka di Jakarta yang menjadikan kota ini seperti kota metropolitan lainnya, pikiran kita telah diarahkan untuk melihat ayam goreng Kentucky Fried Chicken sebagai sebuah entitas yang utuh. Pemikiran ini diarahkan dengan cara sistematis. Sebuah ayam goreng KFC tidak dimaknai sebagai sebuah ayam goreng yang dimasak dengan cara dibalut dengan tepung yang sudah dicampur dengan beberapa bumbu tertentu, baru kemudian digoreng dalam minyak panas, dan proses ini bisa dilakukan siapa saja serta di mana saja. Lalu ayam-ayam ini secara sengaja diberi label dan dijual oleh waralaba yang dulunya lahir di kota Kentucky, Amerika Serikat. Kita merasa bahwa ayam goreng tepung memiliki relasi yang kuat dengan KFC. Ayam goreng tepung adalah KFC dan KFC adalah ayam goreng tepung. Dengan demikian usaha kita mencari yang orisinal dalam sepotong ayam goreng tepung, seperti yang tertulis dalam judul ini, adalah suatu hal yang sia-sia. Padahal secara substansi, tidak pernah ada ayam goreng tepung yang orisinal maupun yang imitasi, karena semua penilaian ini merupakan proses bentukan yang terus membentuk preferensi kita tentang budaya makan. Mungkin justru sebaliknya, mengapa kita tidak berfikir bahwa semua ayam goreng tepung yang ada di dunia ini adalah orisinal?
CATATAN KAKI
[1] Restoran ayam Olive adalah restoran yang menu utamanya berupa ayam goreng tepung dan nasi. Terdapat di beberapa tempat dengan sistem cabang di kota Yogyakarta maupun kota-kota sekitarnya seperti Solo dan Magelang.
[2] Savarin, Jean Anthelme Brillat. 2004. The Physiology of Taste. The Project Guttenberg Ebook, hal.44
[3] Montanari, Masimmo. 1949. Food is Culture, hal. 61-62
[4] Dikutip dari http://www.kfcindonesia.com/kegiatan-usaha-perusahaan
[5] Yan, Yungxiang. 1999. Dalam jurnal Of Hamburger and Social Space: Consuming McDonald’s in Beijing.
[6] Ibid.
[7] Mariani , John F. The Encyclopedia of American Food and Drink, hal. 305-6
REFERENSI BACAAN
Boon, Marcus. 2013. Memuliakan Penyalinan, Terjemahan dari Judul Asli: In Praise of Copying. Yogyakarta : Kunci Cultural Studies.
Caunihan, Carol dan Esterik, Penny Van. 2013. Food and Culture; A Reader. Third Edititon. London: Routledge.
Ritzer, George. 1993. The McDonaldization of Society. California: Pine Forge Press.
Savarin, Jean Anthelme Brillat. 2004. The Physiology of Taste. The Project Guttenberg Ebook.
Schlosser, Eric. 2004. Negeri Fast Food Terjemahan dari Judul Asli: Fast Food Nation oleh Ronny Agustinus. Surabaya: Intipress.